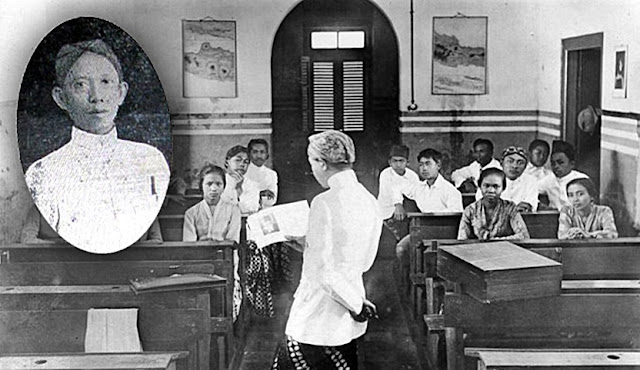Oleh: SINDHUNATA - 20 November 2019
Sindhunata - KOMPAS/FERGANANTA INDRA RIATMOKO
Ya, terhadap politik kita sekarang, rakyat kiranya boleh
merasa patah hati. Rasanya, kita memang sedang hidup di zaman ewuh-pekewuh, di
mana banyak hal jadi serba salah, apalagi politiknya, yang wr-wr-wr, ambyar.
Seribu kota sudah kulewati. Seribu hati sudah kutanyai.
Tapi tak seorang pun mengerti, ke mana kau pergi. Bertahun-tahun aku mencari,
belum kutemukan kau juga sampai hari ini. Seandainya kau sudah hidup bahagia,
aku sungguh rela. Namun hanya satu permohonanku, aku ingin bertemu denganmu.
Walau hanya sekejap mata, sekadar untuk obat rindu di dalam dada.
Itulah sepenggal lagu di antara sekian lagu Didi Kempot
yang akhir-akhir ini telah mengharu biru penggemarnya. Lagu-lagu Didi Kempot
tercipta dalam bahasa Jawa. Dan sudah lama ia menyanyikannya. Namun, baru
akhir-akhir ini lagu-lagunya meledak. Penggemarnya meluas, tak terbatas mereka yang
mengerti bahasa Jawa. Bukan hanya orangtua yang gemar lagu campur sari,
melainkan juga anak-anak muda bergaya hidup modern dan jauh dari tradisi.
Mengapa lagu-lagu Didi Kempot bisa memeluk demikian
banyak penggemar? Karena lagu-lagunya mendendangkan patah hati, cinta yang
dikhianati, dan janji yang mudah diingkari. Luka-luka hati itu banyak dialami
orang zaman ini. Dan Didi Kempot dirasa bisa mewakili dan menumpahkan perasaan
mereka.
Maka kaum patah hati itu berkelompok. Yang laki-laki
menamai diri Sad Bois, yang perempuan Sad Gerls. Keduanya berhimpun di bawah
nama Sobat Ambyar. Dan pujaan mereka, Didi Kempot, digelari The Godfather
of The Broken-Heart alias The Lord of Ambyar.
Ribuan penonton menyimak lagu-lagu yang dibawakan penyanyi pop
campursari Didi Kempot saat tampil sebagai penutup hari pertama perhelatan
Synchronize Fest 2019, Jumat (4/10/2019). Festival musik yang memasuki
penyelenggaraan keempat itu semakin beragam menyuguhkan aneka jenis musik,
mulai dari dangdut koplo, kasidah, metal, sampai disko. - KOMPAS/HERLAMBANG
JALUARDI
Ambyar, kata ini sudah jelas dengan sendirinya. Namun,
mengapa kata itu tiba-tiba bisa demikian populer? Lebih-lebih kenapa ambyar itu
bisa mewakili perasaan demikian banyak orang? Adakah kata itu hanya menyangkut
romantisisme orang di sekitar kesedihan patah hati? Kalau kita bisa bertanya
demikian, berarti suatu makna yang dalam ada di dalam kata ambyar.
Dan ambyar itu tak bisa hanya dikembalikan ke pengalaman patah hati
belaka.
Ambyar seakan adalah kata yang diberikan oleh
keadaan zaman agar kita merasakannya secara lebih luas dan mendalam. Ambyar tak
cukup dikembalikan pada Didi Kempot lagi. Zaman hanya meminjam ambyar-nya
Didi Kempot untuk mengungkapkan gejala dan warta sejarah yang sedang kita alami
kini.
Zaman hanya meminjam ambyarnya Didi Kempot untuk
mengungkapkan gejala dan warta sejarah yang sedang kita alami kini.
Petaka kemajuan
Dalam khazanah Jawa, sebagai gejala sejarah, ambyar membuka
kembali apa yang tersimpan dalam ramalan pujangga Ranggawarsita seperti
tertulis dalam Serat Sabda Jati: Para djanma sadjroning djaman
pekewuh, kasudranira andadi, dahurune saja darung, keh tyas mirong murang
margi, kasetyan wus nora katon—di zaman serba susah dan salah ini, nista budi
manusia makin menjadi-jadi, ruwetnya hidup terus terjadi, orang-orang sengaja
menempuh jalan yang salah, kesetiaan tiada lagi bisa dilihat mata.
Didi Kempot saat menjadi bintang tamu pada sebuah pentas
dangdut di lapangan Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa
Tengah, Selasa (30/7/2019). - KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Rupanya ramalan Serat Sabda Jati tentang
datangnya zaman pekewuh, zaman ruwet, zaman ambyar sedang kita
alami sekarang.
Di zaman ambyar ini manusia jadi serba salah.
Dan seakan ada sebuah kekuatan tersembunyi yang sedang menjerat manusia untuk
jadi serba salah.
Zaman ambyar itu bukanlah ramalan akan masa
mendatang. Ambyar itu petaka di zaman sekarang. Dan ambyar itulah
yang menentukan apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk cita-cita manusia
tentang kemajuan.
Maka, kata filsuf Sekolah Frankfurt, Walter Benyamin:
pengertian kemajuan itu dasar dan titik berangkatnya adalah petaka. Apa yang
terus berjalan maju adalah petaka itu. Dan petaka itu bukan apa yang akan
datang, melainkan apa yang terjadi sekarang. Kalau kita bicara penyelamatan,
ini hanyalah lompatan-lompatan kecil dari petaka yang terus berkesinambungan
itu.
Menurut garis pemikiran itu, masa depan yang gemilang
hanya utopia. Yang akan terjadi adalah masa depan sebagai petaka. Atau dalam
khazanah Jawa, masa depan itu zaman ewuh-pekewuh, zaman ambyar.
Dalam literatur Barat, tulisan mengenai petaka atau ambyar itu
dengan mudah ditemukan, mulai dari tulisan-tulisan filsafat, sosiologi kritis,
politik, ekologis, sampai analisis psikologis, sastra, dan refleksi teologis.
Jadi, bencana atau ambyar itu tak hanya mengenai alam dan lingkungan
hidup, tetapi juga mengenai manusia, pemikiran, rasionalitas, dan kondisi
psikisnya.
Warga Jalan Agung Perkasa, Sunter Jaya, Jakarta Utara, memasang spanduk
protes terhadap penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
Senin (18/11/2019) siang.- KOMPAS/STEFANUS ATO
Petaka atau ambyar dibahas dengan tajam,
misalnya, oleh Pankaj Mishra, sarjana keturunan India, dalam bukunya yang
terkenal Age of Anger: a History of the Present (2017). Ia
menunjukkan, akar dari chaos, petaka dan ambyar-nya zaman ini
adalah utopia enlightenment masyarakat Barat. Utopia itu impian indah
yang akhirnya mendarat sebagai realitas mimpi buruk di zaman sekarang.
Enlightenment dengan buahnya kapitalisme dan
demokrasi liberal ditanamkan ke negara-negara yang tak punya akar tradisi
enlightenment Barat.
Penanamannya sering dengan tindakan paksa: invasi
militer, yang percaya, setelah itu demokrasi akan mekar dengan sendirinya.
Zaman ambyar itu bukanlah ramalan akan masa
mendatang. Ambyar itu petaka di zaman sekarang. Dan ambyar itulah
yang menentukan apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk cita-cita manusia
tentang kemajuan.
Utopia enlightenment mendambakan kemajuan dan
kemodernan. Namun, sebaliknyalah yang terjadi: anti-kemodernan. Di banyak
negara, anti-kemodernan ini berhimpun menjadi aksi radikalisme agama,
kekerasan, dan teror.
Menurut Mishra, aksi-aksi itu bukan pertama-tama
bertujuan merusak kemapanan yang dimiliki kemajuan dan kemodernan. Sebaliknya,
aksi-aksi itu ingin menikmati kemapanan itu. Namun, alam semesta sebagai sumber
daya yang terbatas ini pasti tak bisa memberikan apa yang ingin mereka nikmati,
apalagi semuanya itu sudah berada di tangan mereka yang maju dan modern.
Akibatnya adalah ressentiment, kebencian. Maka,
Mishra mengetengahkan pentingnya kita memahami kembali pemikiran filsuf
Rousseau dan Nietzsche.
Keduanya berpendapat, ressentiment terjadi
karena pengalaman inferior, yang kemudian mengecamukkan perasaan iri hati.
Maunya meniru, tetapi tak mampu.
Hasrat meniru itu terus meninggi, sementara kemampuan
diri kian tertinggal jauh. Janji-janji kemodernan tentang pemerataan akhirnya
hanya mimpi. Si pemimpi kemudian menjumpai realitasnya tak sejalan dengan
impiannya.
Hidupnya merana, dalam hal keadilan, pendidikan, status,
kekuasaan, dan kesejahteraan. Hidupnya ternyata ambyar. Siapa yang mau ambyar?
Maka mereka yang dikecewakan ini frustrasi. Karena frustrasi, mereka lalu
marah, protes, jadi radikal, dan tak segan menjalankan aksinya dengan
kekerasan. Itulah kemarahan kaum ambyar dalam the age of anger ini.
Polisi menjaga ketat penggeledahan rumah keluarga YF, terduga teroris,
di Desa Bojong Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebom, Jawa Barat, Senin
(14/10/2019). YF merupakan pimpinan Jamaah Ansharut Daulah di Kabupaten dan
Kota Cirebon. - KOMPAS/KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Lunturnya
kesetiaan
Di zaman ini, ambyar tak hanya menyambar
politik, ekonomi, ataupun lingkungan. Hubungan personal pun ikut ambyar.
Dalam hal personal itu, lagu-lagu mellow Didi Kempot tentang patah
hati seakan membahasakan dan melokalkan krisis kesetiaan yang kini tengah
menyebar di mana-mana.
Seperti dilaporkan Stephanie Schramm (die Zeit,
7/4/2011), sebuah studi dari Hamburg dan Leipzig, Jerman, pernah
memperlihatkan, 90 persen responden menyatakan ingin tetap setia ke pasangan,
tetapi 50 persen mengaku setidaknya sekali pernah melanggar kesetiaan itu.
Dewasa ini masuknya ”orang ketiga” jauh lebih mudah daripada dulu.
Di zaman ini, ambyar tak hanya menyambar
politik, ekonomi atau lingkungan. Hubungan personal pun ikut ambyar.
Setia dianggap bukan hanya setia pada seorang pasangan
seumur hidup. Orang juga bisa merasa setia terhadap ”orang lain” yang sedang
jadi pasangannya pada suatu saat. Kesetiaan itu bisa menjadi serial, kesetiaan
pada pasangan yang berganti-ganti.
Monogami tampaknya kian dirasakan sebagai upaya kultural
yang berlawanan dengan kodrat alami dan manusiawi, yang sulit bersetia pada
seorang saja.
Teater Baru membawakan lakon Kisah Bunga Matahari di Gedung Kesenian
Jakarta, Jumat (18/10) malam. Para pemain membawakan sketsa-sketsa yang
menggambarkan potret kehidupan keseharian manusia urban yang ”gila gawai”,
menghabiskan waktu di jalanan macet, di bawah tekanan ekonomi, dan diwarnai
perselingkuhan - KOMPAS/INDIRA
PERMANASARI
Karena itu kesetiaan monogami itu sulit dihayati. Juga di
kalangan anak muda melebarlah jurang pemisah antara keinginan dan kenyataan di
sekitar kesetiaan. Mereka menjunjung tinggi kesetiaan. Namun, praktiknya,
dengan mudah mereka berganti pacar atau pasangan.
Fakta ini mengungkapkan sebuah ironi: anak muda ingin
berpegang sungguh pada kesetiaan dan mengidealkan kesetiaan sebagai pegangan,
justru karena dalam realitas kesetiaan itu sedang ambyar dan sulit dialami.
Studi itu juga memperlihatkan, perselingkuhan banyak
terjadi kebanyakan karena si pelaku tertarik akan yang baru. Hubungan dengan
pasangannya bisa memuaskan, juga secara seksual. Namun, itu tak menjamin bahwa
orang tak bisa tertarik dan kemudian puas dan nikmat dengan yang baru.
Lunturnya kesetiaan semacam ini sering disebabkan oleh
sebuah kebetulan, bukan karena disengaja atau direncanakan. Sementara
kesempatan untuk jatuh dalam kebetulan itu sekarang tersedia banyak. Sebab,
dewasa ini manusia lebih mobile, berpindah dari satu tempat ke tempat lain
dengan amat cepat, dan dapat berjumpa dengan ”orang baru” dalam waktu amat
singkat.
Lewat internet, orang juga mudah menemukan rangsangan
akan yang baru, yang sangat bervariasi dan menarik. Dan itu bisa dialaminya
dalam ruang paling privat, bahkan di saat ketika orang berada dekat dengan
keluarga atau pasangannya.
Menurut banyak penelitian, psikologi, sosiologi atau
antropologi, ketidaksetiaan itu ditentukan banyak faktor. Dan sulitlah
memastikan manakah faktor yang paling menentukan.
Kata seorang pakar terapi keluarga, Guy Bodenmann,
kesetiaan adalah proses kognitif di mana orang menghasratkan sebuah
eksklusivitas. Dan itu mengandaikan bahwa orang mau secara total memberikan
komitmennya, emosional dan seksual .
Komitmen demikian butuh kehendak yang kuat dan bulat. Itu
artinya untuk menjadi setia, orang harus bersedia dan rela berkorban untuk
memberikan dirinya. Justru pengorbanan macam inilah yang sekarang sedang
luntur. Tak heran jika kini banyak kesetiaan yang ambyar.
Itu artinya, untuk menjadi setia, orang harus bersedia
dan rela berkorban untuk memberikan dirinya.
Sinetron politik
”ambyar”
Seperti dalam cinta, kesetiaan juga merupakan nilai dalam
politik. Maka dalam ilmu politik, kesetiaan disebut sebagai keutamaan politik.
Politik yang baik tercipta jika politikusnya setia pada janji politiknya, setia
pada konstituennya, dan setia pada mitra koalisinya dalam mengejar cita-cita
yang disepakati bersama.
Jelas, politik yang baik mengandaikan kesetiaan. Apabila
menjunjung tinggi nilai itu, politik serta-merta akan mewujudkan kesetiaan
dalam komitmen, serta pemberian dan pengorbanan diri yang jujur dan tulus.
Namun, justru dalam politik, orang dengan amat mudah mengkhianati kesetiaan,
mengingkari komitmen, dan menjerumuskan diri dalam perselingkuhan politik yang
baru.
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo
Subianto berswafoto dengan wartawan seusai pertemuan keduanya di Istana
Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan tersebut membicarakan sejumlah
isu aktual, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Pertemuan
tersebut juga sebagai penjajakan untuk bergabung atau tidaknya Pantai Gerindra
dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo - KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Jadi, persis seperti atau melebihi perkara cinta,
kesetiaan dalam politik itu mudah terjangkiti virus ambyar. Cuma kadar
akutnya saja berbeda-beda. Kadang akutnya tak seberapa, kadang menggila.
Celakanya, ada gejala, berbarengan dengan merebaknya virus ambyar bersama
Didi Kempot, akhir-akhir ini politik kita kelihatan juga terkena virus ambyar dengan
sangat akut.
Maka, kalau orang percaya pada kawruh Jawa, mewabahnya
Sobat Ambyar Didi Kempot itu juga sasmita yang memperbolehkan kita bertanya,
jangan-jangan situasi sosial-politik kita juga sedang ambyar.
Dengan mudah, ambyar itu kita temukan dalam
tingkah laku politik kita akhir-akhir ini. Kita boleh lega melihat Prabowo
Subianto dan Presiden Jokowi bersatu, dan Gerindra masuk dalam Kabinet
Indonesia Maju (KIM).
Namun, pertanyaan kritis tetap boleh muncul: sebegitu
mudahkah politikus lupa akan pengorbanan pendukungnya. Di manakah kesetiaan dan
komitmen politik mereka pada harapan pendukungnya?
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan presiden terpilih, Joko
Widodo, saling berjabat tangan seusai bertemu di rumah orangtua Prabowo di
Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2019). KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Maklum, sebelum Pilpres 2019, pendukung kedua kubu
demikian terbelah, sampai tak terbayangkan sama sekali bahwa pemimpin mereka
mau menjalin sebuah koalisi politik.
Politik memang punya 1001 alasan untuk membenarkan diri.
Namun, dalam fenomena politik di atas tetaplah terbukti, politik itu tak setia
pada janji. Tepatlah jika para pendukungnya merasakan pahitnya lagu ”Cidra”,
Didi Kempot: ”Wis samesthine ati iki nelangsa/wong sing tak tresnani mblenjani
janji/Gek apa salah awakku iki, kowe nganti tego mblenjani janji/… (Sudah
semestinya hati ini merana karena yang aku cintai mengingkari janji… Apa
salahku, sampai kamu tega mengingkari janji).
Politik yang baik tercipta jika politikusnya setia pada
janji politiknya, setia pada konstituennya, dan setia pada mitra koalisinya
dalam mengejar cita-cita yang disepakati bersama.
Sinetron ambyar di panggung politik itu terus
berlanjut. Baru saja menyatakan janji setia pada koalisi, Ketua Umum Partai
Nasdem Surya Paloh berpelukan mesra dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Sohibul Iman.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) bersama Presiden Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman berangkulan di DPP PKS, Jakarta, Rabu
(30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan
menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. - ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Media pun ramai dengan adegan itu. Presiden Jokowi pun
menyindir, Surya Paloh kelihatan lebih cerah dari biasanya sehabis berpelukan
dengan Sohibul.
Dan Presiden Jokowi masih memberi komentar, ”Saya
tidak tahu maknanya apa. Tetapi rangkulan itu tidak seperti biasanya. Tidak
pernah saya dirangkul oleh Bang Surya Paloh seerat dengan Pak Sohibul Iman.”
Belakangan, pada perayaan HUT ke-8 Parta Nasdem, bahasa
pelukan itu masih berlanjut. Berulang kali Presiden menegaskan, pelukan itu tak
ada salahnya. Toh, Presiden masih menyindir juga, pelukan itu hanya masalah
kecemburuan.
Begitulah, diskursus politik kita diturunkan derajatnya
menjadi masalah pelukan. Sebagian waktu politik kita disita untuk berspekulasi
tentang pelukan. Bahasa politik kita menjadi bahasa Sobat Ambyar. Surya Paloh
menyatakan ”sayang” kepada para tokoh. ”Dan jangan ragukan lagi,
betapa saya masih sayang kepada Mbak Mega.” Megawati memperlihatkan senyumnya
yang tertahan mendengar sapaan itu.
Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandengan dan
melambaikan tangan. KOMPAS/PRADIPTA PANDU
Namun, orang tahu ini sinetron politik, senyum itu boleh
ditafsir sebagai senyum sinis tak percaya. Di mata banyak pemirsa, senyum itu
seakan mau bilang, ”mbel”. Atau dalam bahasa Sobat Ambyar, senyum itu
adalah lagu: Jebule janjimu jebule sumpahmu, ra biso digugu (Janjimu,
sumpahmu, ternyata palsu). Jika bersama dengan fenomena ambyar, kita mau
diingatkan akan sasmita zaman ewuh-pekewuh kita haruslah waspada,
kepalsuan dan ketaksetiaan akan janji kelihatan akan menjadi warna dari politik
kita.
Lihat saja, Pemilu dan Pilpres 2019 baru saja berlalu.
Tokoh-tokoh politik sama sekali belum membuktikan diri apakah mereka bisa
memenuhi janjinya dari kampanye lalu. Kabinet Indonesia Maju juga belum
terbukti kerjanya. Di tengah keadaan demikian sudah terbaca bagaimana politik
membuat manuver-manuver agar mereka bisa mempertahankan atau meraih kekuasaan
di 2024.
Buat politikus kita, demokrasi seakan hanyalah alat
mengejar kekuasaan. Ini sungguh politik ambyar. Ambyar karena
politik itu menghilangkan jejak dan dasar kelahirannya. Seperti dikatakan
filsuf Richard David Precht, politik itu tak lahir dengan sendirinya. Politik
itu lahir dari kepercayaan dan kejujuran rakyat.
Satu hari setelah dilantik, para menteri Kabinet Indonesia Maju
langsung mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko
Widodo bersama Wakil Presiden Ma’aruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis
(24/10/2019). - KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Rakyat lalu mengharap agar berdasarkan kepercayaan itu
politik bertindak bijak, setia, dan tahu diri. Politik yang hanya mengejar
kekuasaan berarti menyapu habis dasar kelahirannya itu. Tak peduli dengan
kepercayaan dan kejujuran rakyat, prek dengan kesetiaan dan kebijaksanaan.
Yang penting, pokoknya, bagaimana meraih kekuasaan.
Politik tak lagi berpikir apa yang terbaik untuk rakyat
yang memercayai dan menumpahkan harapan padanya. Yang dipikirkannya hanyalah
apa yang terbaik bagi dirinya dan itulah adalah semakin besarnya kekuasaan.
Politik yang hanya mengejar kekuasaan berarti menyapu
habis dasar kelahirannya itu.
Politik demikian politik yang tak setia janji. Itulah
politik yang sekarang kira rasakan. Maka terhadap politik demikian, bersama
Sobat Ambyar, rakyat kiranya boleh memaki: Tak tandur pari, jebul tukule
malah suket teki (Padi yang kutanam, ternyata tumbuhnya malah
alang-alang).
Ya, terhadap politik kita sekarang, rakyat kiranya boleh
merasa patah hati. Rasanya, kita memang sedang hidup di zaman ewuh-pekewuh, di
mana banyak hal jadi serba salah, apalagi politiknya, yang wr-wr-wr, ambyar.
Editor, HARYO DAMARDONO