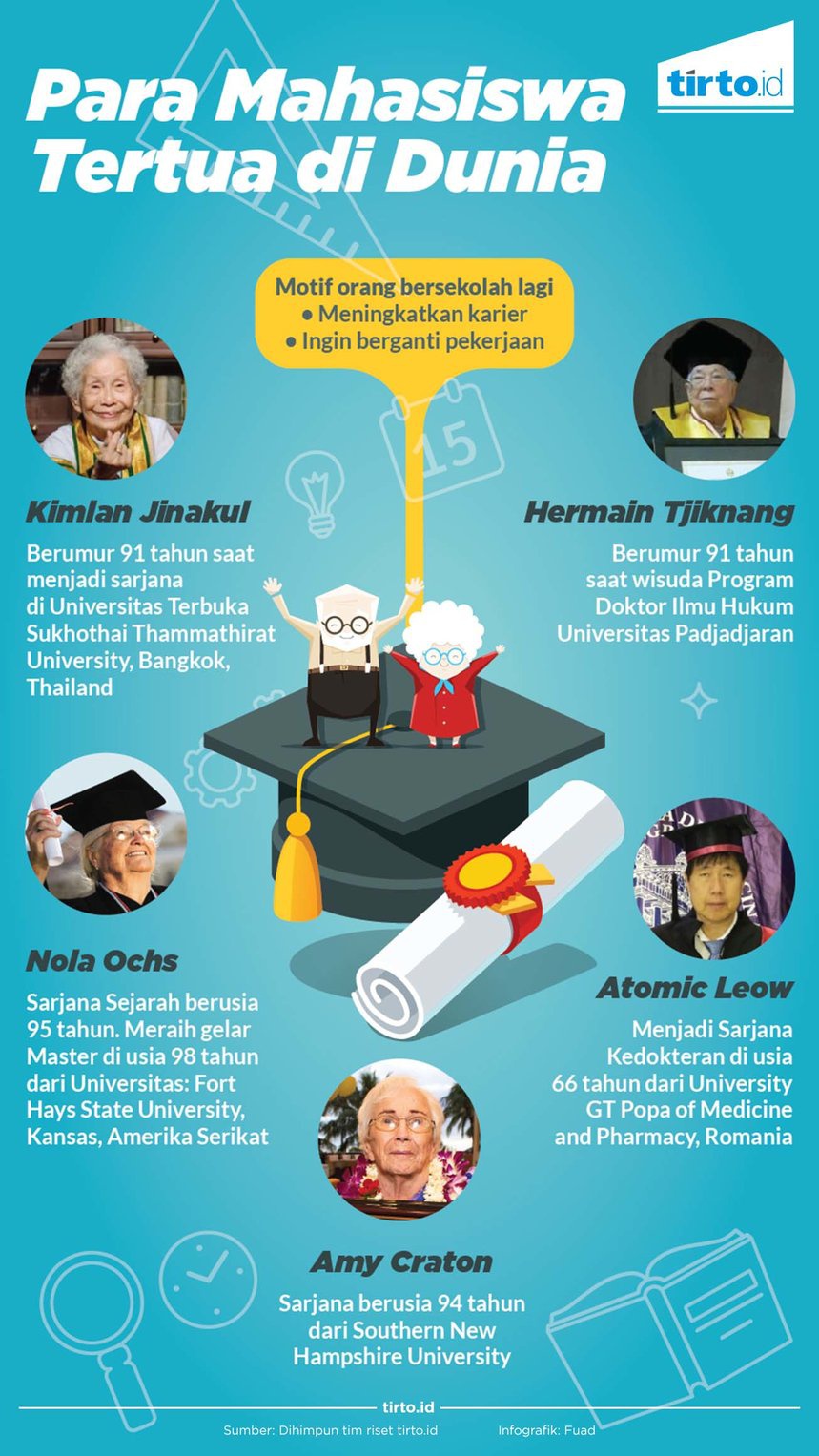Penulis: Noviyanto Aji | 31 Agustus 2017
Lukisan Pangeran
Diponegoro ditangkap dan diasingkan oleh De Kock.
Mataraman – Sejak penangkapan Pangeran Diponegoro
oleh De Kock dan kemudian diasingkan, pahlawan Goa Selarong ini menghembuskan
nafas dalam kesunyian. Benar-benar tragis. Ia dijauhkan dari peradaban pasca
perang Jawa yang terkenal itu. Ia jauh dari sanak dan pengikutnya.
Hingga akhirnya pangeran yang memiliki nama asli
Ontowiryo ini wafat pada Senin 8 Januari 1855, di usia 73 tahun (versi lain
usia 69 tahun). Jenazahnya dikuburkan di luar Benteng Rotterdam, di kampung
Melayu sebelah utara Ujungpandang (sekarang Makasar).
Sejak perang Jawa pecah tahun 1825-1830, pamor Pangeran
Diponegoro telah naik dari bangsawan Mataram menjadi messiah tanah Jawa. Betapa
tidak, ia telah memimpin gerakan perlawananan sporadis alias kraman terbesar
sepanjang sejarah kolonialisme Hindia Belanda di tanah Jawa.
Tidak hanya jatuh korban besar di kedua belah pihak,
tetapi akibat perang tersebut telah menghabiskan pundi-pundi kerajaan Belanda.
Selama perang kerugian pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20
juta gulden.
Perang Jawa ini setidaknya telah memakan korban di pihak
pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi,
dan 200.000 orang Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut
separuhnya dalam kurun 5 tahun peperangan.
Pasca perang, pengikut Pangeran Diponegoro banyak
meninggalkan jejak. Sejak itu pula sejarah penyebaran agama Islam di abad ke-19
tidak bisa dilepaskan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah
Belanda di berbagai daerah.
Yah, para pengikut Pengeran Diponegoro kemudian
melanjutkan perjuangan sambil menyebarkan agama Islam ke masyarakat yang masih
kental dengan budaya dan agama Hindu Majapahit.
Tidak bisa dipungkiri, perang Jawa telah mengakibatkan
banyak ulama pengikut Diponegoro mati syahid. Namun sisanya menyingkir ke
pedalaman, membuka perkampungan, mendirikan masjid, mengajar ngaji para
penduduk kampung. dan merintis pesantren. Sebagian besar para ulama dan
santri ini mengganti nama dan identitas untuk menghindari kejaran Belanda yang
terus menerus memantau pergerakan sisa-sisa laskar Diponegoro.
Raden Mas Ontowiryo
atau dikenal Pangeran Diponegoro.
Sisa-sisa prajurit Diponegoro dalam taktik mengundurkan
diri ini bergerak menyusuri Kali Progo melalui daerah Sentolo, Godean,
Borobudur, Bandongan, Secang Temanggung, dan akhirnya Parakan, sebuah
persimpangan tapal batas Karesidenan Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang,
Yogyakarta dan Magelang, lalu beralih ke wilayah timur atau Matraman. Dipilihnya
daerah Matraman karena umurnya sudah 208 tahun sejak penyerbuan Kerajaan
Mataram ke Batavia.
Langkah strategis seperti ini ditempuh untuk mengimbangi
taktik benteng stelsel(mendirikan banyak benteng kecil untuk menjepit
gerak langkah pasukan Diponegoro), dalam Perang Jawa, yang sebelumnya mereka
alami. Mereka membuka lahan baru (mbabat alas) bersama pengikutnya maupun
menempati desa-desa yang miskin nilai agamanya.
Di Matraman ini, para pengikut Diponegoro terlebih dahulu
mencari tokoh-tokoh setempat yang dianggap mengetahui asal-usul Matraman dan
akhirnya memperkenalkan diri kepada mereka tentang keberadaan Pangeran Mataram
(tidak menyebutkan nama asli) dan menceriterakan secara umum kondisi kejadian saat
itu.
Adalah Pangeran Djonet atau Raden Mas Djonet
Dipomenggolo, adalah putera pertama Pangeran Diponegoro yang diterima
dengan tangan terbuka dan perlindungan masyarakat Matraman. Di situlah sang
pangeran beserta pengikutnya menetap di Matraman lebih kurang selama dua tahun.
Ikatan Keluarga Pangeran Diponegoro (IKPD) dalam blog-nya
menyebut, Pangeran Djonet sudah sejak kecil ikut rombongan pengungsi bersama
keluarga besarnya ke Goa Selarong, setelah Puri Tegalrejo digempur oleh pasukan
Belanda.
Sehingga dia sudah bisa merasakan bagaimana susahnya
hidup dalam pengungsian dan hanya tinggal di dalam Goa bersama ibu dan
saudara-saudaranya.
Selama menetap di Matraman dalam rangka mempertahankan
diri dari kejaran tentara Belanda, Pangeran Djonet membentuk pasukan (semacam
pengawal Raja) dengan merekrut pemuda-pemuda yang mayoritas keturunan prajurit
Kerajaan Mataram walaupun ada juga dari etnis lain yang juga bergabung dengan
suka rela.
Mendirikan Masjid
dan Pesantren
Dari pesantren kembali ke pesantren, demikian semangat
historis pengikut sang messiah ini. Memang tidak banyak diketahui bagaimana
para ulama dan kyai menjadi elemen penting pengikut Diponegoro. Padahal masa
sebelumnya ulama dan keraton berbatas garis demarkasi gara-gara kedekatan
keraton dengan kolonial yang dicap kafir.
Namun sejarawan asal Inggris yang menekuni penulisan
sejarah Pangeran Diponegoro, Peter Carey menyebut, sebenarnya laskar Pangeran
Diponegoro terdiri dari berbagai elemen. Di samping prajurit yang dilatih
militer, pasukan juga terdiri dari kyai dan ulama yang notabene mempunyai
kemampuan ilmu kanuragan.
Dalam naskah Jawa dan Belanda, Carey menemukan 108 kyai,
31 haji, 15 syeikh, 12 penghulu Yogyakarta dan 4 kyai guru yang turut berperang
bersama Diponegoro.
Ya, setelah pengikut Diponegoro menempati wilayah
Matraman, mereka lantas mendirikan masjid dan pesantren. Jejak-jejak itu dapat
dilihat dengan masih berdirinya pondok pesantren tua di Jawa, terutama Jawa
Timur yang banyak menyimpan kronik-kronik sejarah ini.
Sebut saja di Magetan, terdapat Pesantren Takeran yang
menjadi peninggalan pengikut Diponegoro. Pesantren ini yang didirikan oleh Kyai
Kasan Ngulama (Kyai Hasan Ulama), seorang guru Tarekat Syattariyah, yang juga
merupakan putera Kyai Khalifah, pengikut setia Pangeran Diponegoro. Kyai
Khalifah alias Pangeran Kertopati usai perang mengungsi ke arah timur Gunung
Lawu, Magetan, dan membangun sebuah padepokan agama di Bogem, Sampung,
Ponorogo.
Di pondok yang merupakan cikal bakal Pesantren Sabilil
Muttaqin (PSM), Kyai Hasan melakukan kaderisasi para santri yang kelak juga
banyak mendirikan pesantren lain di berbagai daerah. Berasal dari Bagelen,
Purworejo, trio veteran Perang Jawa: Kyai Nur Qoiman, Nuriman dan Ya’qub,
memutuskan mbabat alas di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.
Di desa ini, tiga bersaudara tersebut mendirikan sebuah
masjid. Keberadaan masjid sederhana ini kemudian berkembang menjadi sebuah
pesantren salaf di era kepemimpinan Kyai Murdiyah alias Kyai Muhammad Asrori,
yang merupakan murid Kyai Kholil Bangkalan. Di era Kyai Asrori, banyak santri
yang datang berguru. Kebanyakan berasal dari wilayah Mataraman dan Jawa Tengah.
Pesantren berusia tua ini sekarang menggunakan nama PP. Qomarul Hidayah.
Sezaman dengan Kyai Khalifah, tak jauh dari situ ada
masjid kuno bernama masjid KH Abdurrahman. Lokasinya di Dusun Tegalrejo, Desa
Semen, Kecamatan Nguntoronadi. Seperti namanya, masjid KH Abdurahman
didirikan oleh KH Abdurrahman pada tahun 1835 Masehi.
“Waktu itu setelah kalah perang melawan penjajah Belanda,
para pengikut Pangeran Diponegoro ini menyebar dan mendirikan masjid yang
dijadikan sebagai tempat pendidikan dan perjuangan termasuk di masjid ini,”
jelas keturunan kelima KH Abdurrahman, KH Gunawan Hanafi.
Masjid KH
Abdurrahman Tegalrejo, peninggalan pengikut Pangeran Diponegoro.
Gunawan menuturkan bahwa KH Abdurrahman merupakan
keturunan keluarga Kraton Padjajaran, Jawa Barat, dan hijrah ke Pacitan, Jawa
Timur, yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Kraton Solo. “Beliau itu memang
berganti-ganti nama sebagai strategi perjuangan agar sulit dicari penjajah,”
kata ketua ta’mir masjid setempat ini.
Demikian pula dengan Pondok Pesantren Tambakberas
Jombang. Keberadaannya tak bisa lepas dari keterkaitan historis dengan perang
Diponegoro. Sebab pendiri dan pembabat alas desa dan Pondok Tambakberas adalah
Kyai Abdus Salam atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Soihah. Dia tak lain
pengikut setia Pangeran Diponegoro.
Ketika mbabat alas, Kyai Abdus Salam bersama
pengikutnya mendirikan sebuah langgar kecil dan pemondokan di sampingnya untuk
25 pengikutnya. Jumlah santrinya dibatasi 25 orang. Pondok ini dikenal dengan
nama pondok selawe alias “pesantren dua puluh lima” atau disebut pondok telu
karena hanya ada tiga unit bangunan.
Di kemudian hari, Bani Abdus Salam mendominasi jaringan
ulama di wilayah Jombang, Kediri, dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan mayoritas
silsilah para kiai di wilayah ini mengerucut pada namanya. Salah seorang
puterinya, Layyinah, dipersunting Kyai Usman yang kemudian menurunkan Kiai
Asy’ari, ayah dari KH. M. Hasyim Asy’ari. Adik Layyinah yang bernama Fatimah
menikah dengan Kiai Said. Pasangan ini dikaruniai putera bernama Chasbullah
Said.
Nama terakhir ini adalah ayah dari KH. A. Wahab
Chasbullah, salah satu pendiri NU. Sedangkan adik Kyai Wahab menikah dengan KH.
Bisri Syansuri, ulama yang berasal dari Pati. Kyai Bisri kemudian berbesanan
dengan gurunya, Kyai Hasyim Asy’ari. Di kemudian hari, pesantren ini menjadi
cikal bakal pesantren besar lain di wilayah Jombang, seperti Tebuireng, Rejoso,
Denanyar, Seblak, dan sebagainya.
Kyai Abdus Salam
pengikut setia Pangeran Diponegoro sekaligus pendiri Pesantren Tambakberas,
awalnya mendirikan sebuah langgar kecil dan pemondokan dengan jumlah santri
dibatasi 25 orang.
Di Kediri, ada saudara tiri Diponegoro, Sabar Iman alias
Kyai Bariman bin Hamengkubowono III. Dia menyingkir dari keratonnya dan memilih
tinggal di kota ini. Dari silsilah Kiai Sabar Iman ini lahir Abdul Ghofur. Di
kemudian hari salah satu putra Abdul Ghofur, Mukhtar Syafa’at, menjadi salah
seorang ulama terkemuka di Banyuwangi. Pesantren yang dirintis, Darussalam,
berkembang dengan ribuan santri. Saat ini, pesantren yang didirikan oleh Kyai
Mukhtar Syafaat diasuh oleh putranya, KH. Ahmad Hisyam Syafaat.
Di Kediri juga terdapat Pesantren Kapurejo yang didirikan
oleh Kyai Hasan Muhyi. Setelah bergerilya di lereng Gunung Lawu, Wilis, dan
Kelud, Kyai Hasan Muhyi (Raden Mas Ronowidjoyo), seorang perwira tinggi dalam
Detasemen Sentot Alibasah Prawirodirdjo, akhirnya mendirikan Pesantren
Kapurejo, di Kecamatan Pagu. Pesantren tua ini banyak menelurkan alumni yang
kemudian mendirikan pesantren di wilayah Nganjuk dan Kediri. Kyai Ahmad Sangi
mendirikan Pesantren Jarak di Plosoklaten, Kyai Nawawi merintis Pesantren Ringinagung,
Kyai Sirojuddin merintis pendirian Pesantren Jombangan, dan beberapa kyai lain
juga mendirikan masjid di berbagai tempat tinggal masing-masing.
Selain itu, ada juga Pesantren Miftahul Ulum, Jombangan,
Tertek, Pare, Kediri, yang didirikan oleh Kyai Sirojuddin, kurang lebih
limabelas tahun setelah penangkapan Pangeran Diponegoro. Kyai Sirojuddin
kelahiran Kudus, bergabung dengan pasukan gerilya Diponegoro beberapa saat
menjelang Perang Jawa pecah. Hingga saat ini, Pesantren Miftahul Ulum dilanjutkan
oleh keturunannya dan fokus pada pengembangan kajian al-Qur’an dan kitab
kuning.
Di Nganjuk, terdapat Pesantren Miftahul Ula, Nglawak,
Kertosono. Pendirinya adalah Kyai Abdul Fattah Djalalain. Ayahnya, Kyai Arif,
adalah cucu Pangeran Diponegoro, karena Kyai Arif adalah putera Kyai Hasan
Alwi, yang merupakan putera Diponegoro dari selirnya. Kyai Arif semasa hidupnya
diburu serdadu Belanda dan sering berpindah tempat. Terakhir, ia menetap di
desa Banyakan, Grogol, Kediri.
Di kemudian hari, Kyai Arif menikah dengan Sriyatun binti
Kyai Hasan Muhyi, pengasuh Pesantren Kapurejo. Dari pasangan ini, Kyai Fattah
lahir. Pada era revolusi fisik, Kyai Fattah yang juga santri Kyai Hasyim Asyari
ini menjadi magnet para laskar rakyat, termasuk Hizbullah dan Sabilillah. Sebab,
beliau banyak memberikan wirid, amalan keselamatan, serta kekebalan bagi para
pasukan yang mau terjun ke medan perang. Kyai kelahiran 9 April 1909 ini juga
menjadikan pesantren asuhannya sebagai markas Hizbullah dan Sabilillah.
Para Pengikut
Menanam Pohon Sawo
Pada akhir perang, para kyai pengikut Pangeran Diponegoro
memang berkumpul dan bersepakat untuk merubah arah perjuangan mereka. Dari
perang fisik menjadi perjuangan di bidang pendidikan.
Mereka berpencar untuk menyebarkan pendidikan Islam di
berbagai penjuru mata angin. Namun ada satu komitmen yang menarik dari pengikut
Pangeran Diponegoro, yakni untuk menandakan semangat persatuan melawan
kemungkaran, setiap lokasi yang mereka diami ditanami pohon sawo. Pohon sawo
ini menjadi penanda jaringan Pangeran Diponegoro masih ada. Makna filosofinya,
pohon sawo dilambangkan sebagai “sawwu sufufakum” yang artinya “rapatkan
barisanmu”.
“Pohon sawo itu tanda jaringan Pangeran Diponegoro. Bila
kemudian muncul perintah untuk bergerak lagi, maka tinggal dicek siapa yang
memerintahkannya itu. Dan bila di depan kediamannya ada pohon sawo, maka itu
menjadi tanda bahwa sang pemiliknya masih merupakan anggota jaringannya,” kata
Carey.
Di kawasan Selatan Jawa atau wilayah Matraman, banyak
sekali anak keturunan Pangeran Diponegoro yang masuk dalam jaringan ulama
karena mereka kemudian menjadi ulama sera mengasuh pesantren. Karena itu di
beberapa pesantren tua di wilayah tersebut biasanya dapat dijumpai pohon sawo
yang usianya sangat tua.
Seperti pohon sawo yang berdiri di Pesantren Al Kahfi
Somalangu, Kebumen. Di sini dapat ditemukan pohon sawo tua, baik jenis sawo
kecik maupun sawo biasa.
Menurut Hidayat Aji Pambudi, pengurus Yayasan Pesantren
Al Kahfi,
“Pohon sawo keciknya baru saja ditebang terkena perluasan halaman pesantren.
Sedangkan, pohon sawo jenis yang biasa masih tumbuh subur di samping masjid,”
katanya.
Pohon sawo yang
berdiri kokok di Pesantren Al Kahfi Somalangu, Kebumen. Di pesantren-pesantren
tua pohon sawo menjadi penanda jaringan Pangeran Diponegoro.
Di tempat lain, tepatnya di Masjid Pathok Negara Ploso
Kuning, Sleman, Yogyakarta, pohon sawo kecik raksasa hingga kini masih berdiri
dengan kokohnya. Masjid ini menjadi salah satu tempat mengaji Pangeran
Diponegoro ketika menjadi santri Kyai Mustofa.
“Dunia orang Jawa kan penuh perlambang atau isyarat. Di
setiap pesantren di wilayah ini memang lazim di tanam pohon sawo sebagai
perlambang dari perintah untuk taat ketika ada perintah: sami’na wa ato’na
(saya mendengar, saya laksanakan),” kata peneliti dunia pesantren di kawasan
Selatan Jawa, Ahmad Khoirul Fahmi.
Fahmi mengutip kata-kata ayahnya soal kalimat sami’na
wa ato’na terutama ketika menjelang dilaksanakannya shalat berjamaah di
masjid.
“Kata Ayah saya, ingat di depan masjid kita itu ada pohon sawo. Itulah
artinya: segera laksanakan ketika kamu dengar perintah!”
Di antara cicit Pangeran Diponegoro atau berdarah
bangsawan Keraton Yogyakara yang kemudian menjadi ulama berpengaruh di wilayah
ini adalah KH Muhammad Ilyas dan KH Abdul Malik (di Sokaraja), KH Badawi (di
Kesugihan Cilacap), KH Masurudi (di Baturaden Purwokerto). Fahmi menambahkan,
di pesantren tua yang diasuh kyai-kyai tersebut pasti ditemukan pohon sawo. Ini
memang menjadi perlambang masih kuatnya jaringan antar ulama yang notabene
mantan pengikut Pangeran Diponegoro.
“Jadi wajar bila banyak pesantren tua yang ada kawasan
ini banyak di tanam pohon sawo, yang ternyata itu isyarat adanya jaringan
ulama,” pungkas Fahmi.
Domini BB. Hera yang kerap dipanggil Sisco, keturunan eks
pasukan Diponegoro yang menyingkir ke Ngantang, perbatasan Blitar-Kediri,
menceritakan di Tegalrejo (Magetan), pohon sawo menjadi representasi sang
pangeran.
Bukan hanya sebagai kode rahasia, lanjut Sisco, para
pengikut Diponegoro mempercayai sawo kecik akan mendatangkan kebaikan bagi
penanamnya.
“Bagi orang Jawa, sawo kecik memiliki arti sarwa
becik atau serba baik. Keraton-keraton pecahan Kerajaan Mataram, seperti
Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, menanam sawo kecik. Kedudukannya
sejajar dengan pohon beringin, asam, dan gayam. Pakubuwana X (memerintah
1893-1939) menanam 76 sawo kecik di lingkungan Kasunanan Surakarta. Sawo kecik
juga banyak ditemukan di Kesultanan Yogyakarta,” terangnya.
Pada masa revolusi kemerdekaan, pohon sawo kecik di
belakang keraton Yogyakarta pernah menjadi tempat berkumpul para pejuang.
Menurut Hardi, salah satu tokoh Partai Nasional Indonesia dan pernah menjabat
wakil perdana menteri I, jika hendak melapor Sultan Hamengkubuwana IX di
keraton, para pejuang menyamar sebagai abdi dalem dengan berpakaian
Jawa, lalu berkumpul di bawah pohon sawo kecik di belakang keraton.
“Jika suasana dianggap aman dari incaran intelijen
Belanda, baru kami buru-buru masuk keraton,” kata Hardi.
Hingga kini tidak terhitung ribuan santri yang menjadi
alumni dan kelak menjadi penerus perjuangan Diponegoro; melawan penindasan dan
kemungkaran. Karena memang begitulah semangat Pangeran Diponegoro seharusnya
diwariskan.[]